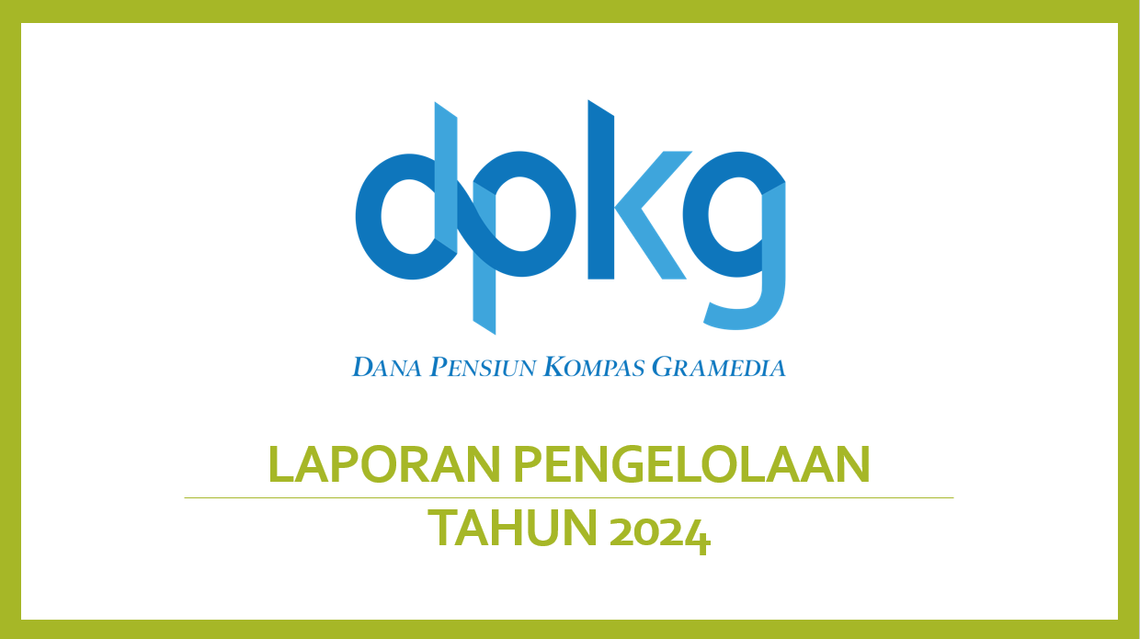Info KG
>
#CumadiKG
#CumadiKG
Kompas dari Masa ke Masa
AGATHA TRISTANTI
Mon Jun 30 2025 02:53:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Corporate Branding Analyst - Dipublikasikan

tulisan oleh: Mamak Sutamat (Wartawan Senior Kompas, Purnarkarya 2004)
Bulan Juni lalu Harian Kompas genap berusia 55 tahun. Bisa dikatakan SUDAH 55 tahun karena dia adalah koran terlama di negeri ini. Tapi bisa juga dikatakan BARU 55 tahun jika dibanding dengan koran-koran besar di mancanegara. Satu hal yang sama: perlu disyukuri!
Saya masuk Kompas sejak 1970, saat Kompas baru berusia 5 tahun dan beroplah 60.000 eksemplar. Saya mengalami kejayaan Harian Kompas dengan oplah 600.000 eksemplar pada 1986. Perjalanan karier saya yang lebih banyak berada di "dapur" Kompas, apalagi kemudian diberi kesempatan untuk menulis “buku” sejarah Kompas, membuat saya mengenal dalam-dalam lembaga ini.
Dalam pengamatan saya, Kompas hingga kini terbagi dalam 3 periode: Periode Awal (persiapan hingga 1972), Periode Pengembangan (1972-1999), dan Periode Peralihan (2000-sekarang). Setiap periode memiliki tantangan sendiri-sendiri dan periode hari ini merupakan penentuan langkah ke depan Kompas cetak.
Periode Awal. Pada persiapan penerbitan Kompas, Pak Jakob dan Pak Ojong sepakat hendak membuat koran umum yang bergengsi dan dipercaya pembacanya. Ketika Kompas semakin besar oplahnya, Pak Ojong malah khawatir, sebab pohon yang tinggi akan lebih gampang dan sering digoyang angin. “Lebih baik kita nomor dua, mengejar lebih bersemangat daripada dikejar,” begitu disampaikan.
Harian Kompas memang “pinaringan Gusti”, given. Jalan untuk maju itu seolah disibakkan oleh berbagai peristiwa yang terjadi: Pemberontakan Gestapu tahun 1965; diikuti pemberedelan koran-koran yang dianggap prokomunis yang notabene koran-koran beroplah besar pada masanya; dan (ini paling utama) memiliki tenaga-tenaga mumpuni yang out of the box pada zamannya. Para wartawannya sungguh berbeda dengan sikap wartawan pada masa itu. Kondisi ini yang membuat Kompas melesat tak terkendali.
Pak Jakob sebagai pemimpin redaksi pun memimpin anak buahnya dengan sangat tegas. Dengan gaya Jawa-nya ia membuat anak buahnya tak berkutik. “Saudara Roby, kalau berita you hanya begini, lebih baik saya kirim Pak Nalik bawa tape recorder,” begitu ia menegur wartawannya yang kemudian hari menjadi wakil pemimpin umum Kompas. Pak Nalik saat itu adalah seorang pesuruh yang sudah berusia lanjut.
Pada saat memulai penerbitannya, duo perintis ini merekrut tenaga-tenaga muda yang tidak berlatar belakang wartawan, terkecuali beberapa redakturnya. Saat itu Pak Ojong menjadi dosen dan aktivis di gereja maka dia pun merekrut para mahasiswanya yang terpilih dan para mahasiswa katolik yang tergabung dalam PMKRI. Pak Jakob yang berasal dari seminari, membawa kawan-kawannya yang sudah keluar, entah itu senior maupun juniornya.
Perpaduan jebolan seminaris dan aktivis mahasiswa ini membawa Kompas menggelinding bagai bola salju. Bagaimanapun, misi dan visi yang sama membuat organisasi bergerak seirama. Mereka bekerja tanpa kenal waktu, mengerahkan energi seutuhnya untuk mengisi koran. Ditambah, hampir semua adalah wartawan muda dan bujangan. Mereka ini tidak memikirkan imbalan tapi lebih memfokuskan pada cita-cita. Bahwa imbalan itu akhirnya datang, mereka tak pernah menggugat besar kecilnya. Para pimpinan itu pun adalah teman-temannya di sekolah atau seminari sehingga di antara mereka seolah tidak ada jarak. Diskusi bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa sama-sama duduk di meja tanpa risi. Keadaan ini sangat mendukung perjalanan Kompas saat itu.
Lembaga pertama di Harian Kompas adalah Redaksi. Saat terbit hingga beberapa tahun, urusan administrasi Kompas diserahkan kepada penerbit majalah Star Weekly yang saat itu sudah diberedel. Majalah tersebut dipimpin Pak Ojong yang segera menyalurkan tenaga pegawai administrasinya untuk mengurus Kompas dengan tetap sebagai karyawan Star Weekly. Jadi, pada awal mula kalau menyebut Kompas, maksudnya ya Redaksi; maklum tidak ada lembaga lain.
Saat masih berkantor di Jalan Pintu Besar Selatan (1965-1972) yang notabene kantor Star Weekly, anggota Redaksi paling banyak mendapat “kejutan”. Begitu mendapat rezeki melimpah, pimpinan segera membagikan sebagian untuk Redaksi hingga ada istilah uang nonton, uang payung, uang susu, bonus, juga amplop kejutan. Kebiasaan ini terbawa terus dan makin meluas untuk para tenaga nonredaksi yang kemudian hari dibentuk.
Pada 1972 Kompas memiliki percetakan sendiri dan kantornya pindah ke Palmerah Selatan. Di sinilah Kompas mulai melejit dan membutuhkan banyak tenaga. Begitu kendala percetakan teratasi, oplah terus naik namun organisasi Redaksi tidak berubah, masih tersentralisasi pada Pak Jakob Oetama yang menggembleng anak buahnya dengan keras. Semangat kerja tetap membara, visi misi pun masih sama.
Periode Pengembangan. Begitu memiliki percetakan sendiri di Palmerah Selatan, tiras Kompas tak terbendung, ditambah dengan adanya regulasi pemerintah dalam menyikapi perkembangan media cetak. Awalnya jumlah halaman dibatasi, bahkan pemasangan iklan pun sempat diatur-atur sehingga perkembangan Kompas tersendat-sendat. Saat itu pimpinan Kompas memprediksi oplah sampai satu juta eksemplar dengan tebal 16 halaman sehari. Kini, giliran percetakan yang dikejar-kejar untuk segera menambah mesin cetak. Padahal membeli mesin cetak saat itu harus pesan beberapa tahun sebelumnya.
Ketika oplah Kompas berhenti di angka 600.000, giliran percetakan melecehkan manajemen Kompas. Untunglah saat itu walau oplah hanya sekitar 600.000, tetapi jumlah halamannya bisa sampai 100 halaman! Dengan demikian, pembelian mesin cetak itu tidak sia-sia.
Bagian Redaksi juga dikejar-kejar karena penambahan jumlah halaman mengharuskan penambahan tenaga pengisinya. Awalnya direkrutlah wartawan melalui sistem “jawilan”, wartawan-wartawan lama merekomendasikan rekan-rekan atau komplotannya. Mereka dibutuhkan karena Kompas membutuhkan wartawan yang siap pakai. Dampaknya, mutu wartawan jadi campur aduk, visi misinya pun kabur karena pendatang baru membawa kebiasaan dari lembaga sebelumnya.
Untunglah saat itu manajemen cepat sadar sehingga menata ulang perekrutan wartawan. Itu terjadi setelah J. Widodo diminta menjadi “rektor” atas pendidikan wartawan Kompas. Di sini para calon wartawan benar-benar disaring (minimal S1 dan berjiwa toleran) serta dididik hingga setahun sebelum dilepaskan menjadi pemburu berita. Kala itu Pak JO menggantikan Pak Ojong menjadi pimpinan umum. Pada 1980 Pak Ojong meninggal mendadak sehingga mau tak mau Pak JO harus menggantikannya dan mengurangi kegiatan di Redaksi.
Setelah bertugas di Persda, pada tahun 2000-an saya sempat menjadi anggota tim perekrut wartawan dalam beberapa periode. Dalam setiap kesempatan, Pak Jakob selalu menekankan perlunya tenaga yang toleran dan berasal dari berbagai daerah sehingga cita-cita menjadikan Kompas sebagai Indonesia Mini terwujud. Begitu pindah di Palmerah Selatan, Redaksi banyak diisi oleh tenaga yang tesnya dilakukan Pak Jakob sendiri. Titik berat tenaga-tenaga ini terutama sikap tolerannya terhadap agama dan pendapat orang lain. Tentu saja juga bobot keilmuannya. Para calon wartawan ini datang dari berbagai penjuru daerah dengan latar belakang yang beraneka ragam.
Pada zaman Menpen Harmoko, terbit ketentuan bahwa perusahaan pers harus berbentuk PT atau koperasi. Karyawannya harus memiliki saham minimal 20 persen di perusahaan penerbitan. Saat itu Kompas diterbitkan oleh Yayasan Bentara Rakyat yang didirikan Partai Katolik, sesuai tuntutan pemerintah agar setiap partai memiliki koran sendiri. Modal Yayasan dari Partai Katolik sebesar lima juta rupiah, selain itu tidak ada yang mengiur termasuk para perintis dan pendiri yayasan. Bahwa dalam perjalanan ada pimpinan yang sempat menggadaikan rumahnya untuk menambah modal, itu berbentuk pinjaman.
Pada 1980 para pimpinan Kompas berunding tentang bentuk badan hukum yang akan menggantikan yayasan. PK Ojong yang sejak awal seorang sosialis mengusulkan bentuk koperasi namun peserta rapat lainnya minta bentuk perseroan terbatas (PT). Rapat pun menemui jalan buntu. PK Ojong minta berhenti sebagai direktur utama tapi ditahan IJ Kasimo. Keputusan pun ditunda. Dua bulan sesudah rapat itu, PK Ojong terkena serangan jantung dan berpulang.
Beberapa tahun kemudian terbentuklah PT Kompas Media Nusantara menggantikan Yayasan Bentara Rakyat. Saat itu pemiliknya adalah Yayasan Bentara Rakyat, Karyawan Kompas, IJ Kasimo, PK Ojong, Jakob Oetama, dan P. Swantoro. Pemilik ganti namun tidak ada perubahan berarti bagi Kompas. Koran tetap berkibar dan para pemilik baru selalu berbaik hati berbagi keuntungan serta rezeki yang melimpah kepada karyawan.
Saya ingat, pada 1995 seusai apel bendera pada peringatan 50 tahun kemerdekaan RI di depan Bentara Budaya, Pak Jakob yang merasa terkesan memanggil pimpinan bagian keuangan, Cherly Piktiyani, dan bertanya, “Kita punya uang untuk memberi hadiah sebulan gaji?” Pertanyaan itu dilontarkan masih di halaman BBJ, saat itu saya berdiri dekat Cherly. Usai apel, langsung diumumkan bonus khusus Hari Kemerdekaan satu bulan gaji buat semua karyawan.
Periode Peralihan. Periode ini ditandai dengan semakin merosotnya oplah koran. Sebenarnya sejak tahun 1980-an beberapa pimpinan Kompas sudah merasa akan hadirnya koran masa depan karena saat itu di seluruh dunia ribut tentang datangnya koran digital. Pimpinan Litbang Kompas saat itu, J. Widodo, sudah memprediksi akan datangnya zaman itu. Namun sepertinya persiapan kita untuk menyongsong perubahan itu kurang cekatan.
Ketika pada tahun 1986 saya diminta mengikuti pelatihan penggunaan komputer System-6 di Inggris, itu pun sudah sangat terlambat. Maklum, untuk memilih sistem komputer yang hendak digunakan saja butuh perdebatan selama bertahun-tahun sehingga ketika saya ikut pelatihan, pabrik komputernya di Jerman sudah tutup. Ironis! Sistem tersebut mampu memotong banyak pekerjaan di Redaksi maupun percetakan.
Perubahan dari koran cetak ke digital begitu cepat. Lalu bagaimana seharusnya Kompas edisi cetak? Almarhum Pak Ojong pada awal pendirian koran ini sudah menekankan ingin membuat koran seperti Le Monde. Oplah kecil tapi bermutu dan berpengaruh sehingga bisa dijual dengan harga mahal. Cita-cita ini memerlukan kerja keras karena harus memodifikasi produk dan tentu saja meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terutama wartawan. Jika bersinergi dengan versi digital, Kompas macam itu adalah keniscayaan. (*)
Please login to continue reading
Please login to continue reading
Likes
I WAYAN SUKRA SUDIARSA
003728 - I WAYAN SUKRA SUDIARSA
Likes
Likes
I WAYAN SUKRA SUDIARSA
003728 - I WAYAN SUKRA SUDIARSA
Are you sure want to submit your article?
You cannot edit your article after you submit it.
Are you sure want to submit your article?
You cannot edit your article after you submit it.
Are you sure want to delete your comment?
Recommended
#CumadiKG
Dukung Pencegahan Penularan Covid-19, Kompas Gramedia Gelar Vaksinasi Booster untuk 2.000 Karyawan
BRIANTI NOVIRANDANI